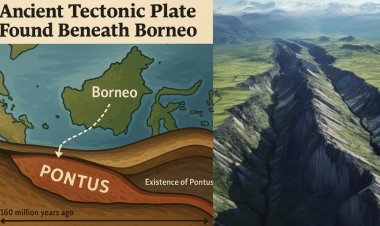Upah Tak Cukup Hidup, Denpasar di Ambang Ledakan Sosial

DENPASAR — Lonjakan angka bunuh diri di Bali, khususnya di Kota Denpasar, dinilai sebagai sinyal darurat dari krisis ekonomi yang kian menekan masyarakat. Persoalan ini disebut bukan semata soal kesehatan mental, melainkan buah dari ketimpangan serius antara upah dan biaya hidup yang dibiarkan berlarut-larut.
Pengamat sosial sekaligus Sekretaris Organisasi ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan atau yang akrab disapa Gung De, menegaskan bahwa struktur ekonomi di Denpasar sudah berada pada fase berbahaya. Ia menyoroti penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Denpasar 2026 yang berada di kisaran Rp3,5 juta per bulan, jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai sekitar Rp5,2 juta.
“Ini bukan selisih kecil. Ini jurang. Artinya sejak hari pertama menerima gaji, pekerja sudah hidup dalam kondisi defisit,” ujar Gung De. Menurutnya, selisih hampir Rp2 juta per bulan adalah ketimpangan ekstrem yang mustahil ditutup oleh pekerja dengan penghasilan tetap.

Ia menjelaskan, beban hidup warga Bali tidak berhenti pada kebutuhan pokok seperti pangan dan tempat tinggal.
Biaya pendidikan yang tinggi, ditambah kewajiban adat dan budaya—mulai dari pembelian pakaian endek hingga kursus tari dan tabuh bagi anak—menjadi tekanan tambahan yang tak bisa dihindari oleh keluarga.
Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya transportasi publik yang layak. Warga akhirnya dipaksa bergantung pada kendaraan pribadi, lengkap dengan cicilan dan biaya operasional yang terus menggerus pendapatan. “Ini tekanan berlapis. Negara dan pemerintah daerah seolah menormalisasi situasi yang jelas-jelas tidak adil,” kata Gung De.
Ia membandingkan situasi Denpasar dengan Jakarta, di mana upah minimum berada di kisaran Rp5,7 juta dan KHL sekitar Rp5,8 juta. Selisih yang tipis itu, menurutnya, menunjukkan kebijakan pengupahan yang jauh lebih realistis dibandingkan Denpasar yang justru memiliki biaya hidup tinggi sebagai kota pariwisata internasional.
“Denpasar dipromosikan sebagai kota kelas dunia, tapi upah buruhnya diperlakukan seperti daerah berbiaya murah. Ini ironi sekaligus kegagalan kebijakan,” tegasnya.
Gung De memperingatkan bahwa ketimpangan ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan ancaman sosial jangka panjang. Meningkatnya angka bunuh diri disebutnya sebagai gejala awal dari krisis struktural yang lebih dalam.
“Kalau pemerintah terus menutup mata, maka Bali sedang duduk di atas bom waktu. Korban akan terus berjatuhan, dan itu bukan lagi tragedi personal, melainkan tragedi sosial,” pungkasnya.
Editor: Ray