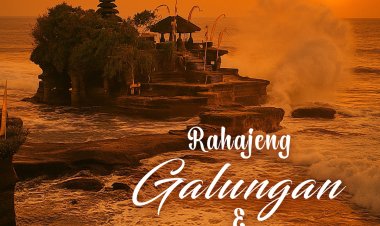Banjir Bali, Retaknya Harmoni Manusia dan Alam

Oleh: Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
DENPASAR - Banjir yang berulang melanda Bali tidak bisa lagi dipandang sebagai fenomena musiman belaka. Ia adalah cermin pecahnya relasi manusia dengan alam, tanda bahwa keseimbangan yang diwariskan leluhur kian rapuh.
Dalam ajaran Tri Hita Karana, keseimbangan hidup berdiri di atas tiga pilar: parhyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), pawongan (hubungan antarsesama), dan palemahan (hubungan manusia dengan alam). Kini, palemahan tampak terabaikan.
Alam yang Dikorbankan
Demi kepentingan jangka pendek, Bali mengalami eksploitasi yang nyaris tanpa rem. Sawah-sawah yang dulu menopang sistem subak dan menjadi benteng ekologi berubah menjadi deretan vila, hotel, serta pusat perbelanjaan.
Hilangnya lahan resapan membuat air hujan kehilangan ruang untuk meresap. Akibatnya, air meluap ke jalan, permukiman, dan kawasan wisata. Ironis, wilayah yang dahulu sumber pangan justru kini menjadi pemicu bencana.
Alih fungsi lahan tak terkendali berarti mengabaikan kearifan lokal. Lebih buruk lagi, ia menyeret masyarakat Bali dalam lingkaran banjir tahunan yang semakin parah.
Sungai yang Tercemar, Kearifan yang Terlupakan
Sungai dalam tradisi Bali adalah entitas sakral, simbol kesucian kehidupan. Namun kenyataan hari ini, sungai diperlakukan bak tempat sampah raksasa. Plastik, limbah rumah tangga, hingga sisa industri menumpuk, menyumbat aliran.
Saat hujan deras turun, sungai meluap, membawa lumpur dan kotoran yang merendam rumah hingga objek wisata. Sungai yang dulu sumber kehidupan kini berubah menjadi sumber penyakit, kerusakan ekosistem, dan turunnya kualitas air bersih.
Peringatan dari Alam
Banjir, longsor, hingga kekeringan yang kian sering terjadi adalah alarm keras dari alam. Seakan-akan alam berujar: ketika manusia mengabaikan palemahan, bencana tak bisa dihindari.
Kerusakan lingkungan bukan hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menggerogoti identitas budaya Bali. Apa gunanya melestarikan adat dan upacara jika sumber kehidupan—alam itu sendiri—dikhianati?
Menagih Tanggung Jawab Bersama
Banjir di Bali mestinya dipahami sebagai peringatan, bukan sekadar musibah. Saatnya memulihkan kembali harmoni dengan alam: menata ulang tata ruang, memulihkan hutan dan resapan air, serta mengubah pola konsumsi yang merusak.
Kesadaran ekologis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, Bali hanya akan tersisa dalam brosur pariwisata—indah di mata, rapuh dalam kenyataan.
Jika manusia tetap menutup mata, banjir hanyalah awal. Yang terancam hilang bukan hanya kelestarian alam, tetapi juga roh budaya Bali yang selama ini dijunjung dunia. (Tim)